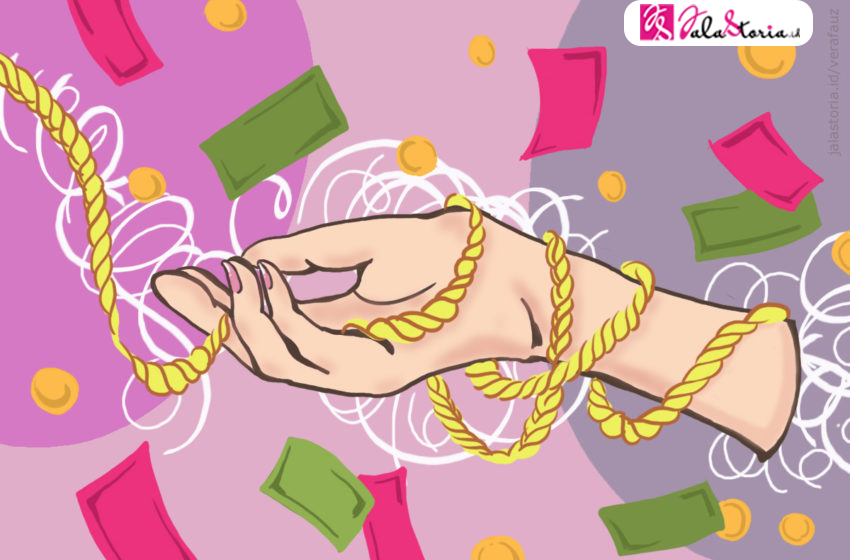Oleh: Ninik Rahayu
Jumlah korban kejahatan perdagangan orang (human trafficking) terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakkan, tak ada jeda waktu untuk mencegah dan menghentikannya. Kondisi ini seolah tidak sebanding dengan aneka perangkat aturan hukum dan segala mekanisme yang dibangun pemerintah. Pelbagai instrumen hukum seakan beku, standard operating procedure (SOP) dan sistem seperti lorong panjang yang tidak bisa menjadi kebijakan untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan para pekerja yang bermigrasi.
Dengan aneka payung peraturan dan sistem yang ada, praktik kejahatan ini terus saja muncul bahkan jangkauannya meluas. Korban tidak lagi hanya perempuan dan anak-anak, bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi cukup banyak, di sepanjang 2010-2016 korban human trafficking dialami laki-laki dan warga asing yang bermigrasi ke Indonesia. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, sekaligus menjadi ironi di tengah melimpahnya aturan hukum yang mengatur perdagangan manusia di Indonesia.
Persoalan human trafficking memang beragam. Dan, seperti biasanya, pemecahan masalahnya sesulit mengurai benang kusut. Barangkali, inilah faktor penyebab tidak ada satu pun institusi pemerintah yang berani dengan tegas mengatakan bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawabnya. Yang ada malah saling mempersoalkan kinerja antarsektor atau departemen antara satu institusi dengan institusi lainnya.
Bangunan sistem kerjasama dan koordinasi antarinstitusi belum terealisasi dengan baik dan maksimal. Sebut saja gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang didukung dengan Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Permeneg PP dan PA Nomor 10/2012 tentang Panduan Gugus Tugas TPPO. Aneka ketentuan tersebut belum secara baik terkoordinasi dan termaksimalkan.
Rekrutmen
Wilayah Indonesia memang luas sekitar 1.990.250 km, dengan 17.504 pulau dan 1.304 suku bangsa, dengan 546 dialektika bahasa yang berbeda. Bila dikaitkan dengan human trafficking, tentu kondisi ini menjadi “peluang” sekaligus menyediakan banyak titik rawan tempat rekrutmen calon tenaga migran. Dan bukan hanya rentan terkait perekrutan, tetapi juga berpotensi menjadi titik transit serta tujuan.
Data nasional korban human trafficking tidak pernah muncul ke permukaan dengan utuh. Selain karena tidak semua korban melapor karena berbagai alasan, unit pelaporan kasus perdagangan manusia belum terbuka lebar. Terutama yang dapat menjamin rasa aman bagi korban, baik sebelum (pelaporan), selama (pelaporan), maupun setelah pelaporan dilakukan. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada institusi yang memiliki “kepedulian” menjadi pusat pengelola data nasional kasus human trafficking.
Padahal, berawal dari data nasional ini dapat disusun roadmap kondisi dan situasi kasus sekaligus perencanaan upaya pencegahan dan penanganan korban. Mekanisme kerja secara komprehensif sangat diperlukan agar tidak ada kesan pembiaran dan keberulangan kasus secara terus-menerus. Pembiaran adalah situasi yang saat ini tergambar oleh kita semua. Salah satu contohnya adalah kasus dan korban human trafficking dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski secara angka, korban human trafficking dari wilayah ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan wilayah Jawa barat dan Jawa Timur tetapi berdasarkan data perdagangan orang (DPO) NTT Tahun 2014 yang diolah Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)-dari liputan tiga koran utama di NTT menunjukkan- 88% dari 1.038 orang menjadi korban perdagangan orang yang dokumennya dipalsukan.
Penemuan informasi terkait pemalsuan dokumen seharusnya bisa menjadi pintu masuk proses penyidikan oleh aparat keamanan berkaitan dengan indikasi korban human trafficking. Begitu pula oleh pemerintah daerah, seharusnya temuan itu bisa menjadi inisiasi untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kondisi warganya yang bermigrasi? Pertanyaannya kemudian: Mengapa data ini menjadi sangat penting?
Dari satu wilayah ini saja, tidak pernah diketahui dengan tepat berapa sebenarnya jumlah warga yang bermigrasi, berapa jumlah yang sudah terlindungi oleh negara, dan berapa yang tidak terlindungi atau bahkan berapa yang sebenarnya sudah dalam kondisi menjadi korban kasus human trafficking. Jika situasi dimaksud belum juga dianggap penting oleh pemerintah, tidak dapat diketahui pula dengan tepat apa yang menjadi faktor penyebabnya, bagaimana kondisi korban dan keluarganya saat ini, bagaimana pula mencegah ini tidak berulang.
Data seharusnya menjadi instrumen penting bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam menangani kasus human trafficking. Menurut IRGSC jika melihat data demografis dan penyebaran TKI asal Indonesia, maka aslinya, jumlah tenaga kerja asal NTT bukan berasal dalam posisi puncak piramida. Namun, mencuatnya kasus perdagangan orang dapat dibaca dalam dua tafsir. Pertama, NTT merupakan target lokasi perdagangan orang. Kedua, kuatnya komponen masyarakat sipil di NTT dalam membuka kasus perdagangan orang mendorong NTT menjadi fokus berita.
PTSP Belum Maksimal
Jika gambaran peristiwa itu terjadi sepuluh tahun lalu, mungkin bisa ditoleransi. Seharusnya sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) melalui UU 21/2007 dan kebijakan terkait Penyelenggaraan PTSP oleh kabupaten/kota melalui Perpres 97/2014 yang merupakan pembaharuan dari pengaturan sebelumnya, seharusnya hal di atas tidak terjadi lagi. Pengaturan PTSP memberikan mandat kepada bupati/walikota untuk memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) kabupaten/kota. Salah satunya soal izin imigrasi, ada praktik yang berbeda antara layanan di front office dengan back office di kantor PTSP. Di front office, masyarakat yang ingin mengurus izin bermigrasi memang hanya dihadapkan pada proses di unit PTSP. Tetapi di back office, misalnya, pekerjaan terkait layanan imigrasi, oleh petugas yang tergabung dalam layanan PTSP akan tetap dikerjakan di kantor imigrasi. Kondisi ini menunjukkan belum adanya sistem penyelesaian satu atap.
Akibat yang muncul kemudian, tentu saja, bukan hanya soal lamanya proses penyelesaian dokumen, tetapi keterpaduan proses untuk memastikan tidak adanya identitas ganda dan lainnya menjadi sulit dilakukan.
Minim Perlindungan
Minimnya data tenaga kerja yang bermigrasi dan model perlindungan yang telah diberikan, maka adanya informasi dugaan human trafficking, bisa beragam model. Salah satunya bisa berawal dari surat yang dikirim oleh salah satu KBRI. Salah satu kasus yang dilaporkan oleh KBRI di Seoul menginformasikan bahwa ada kasus perdagangan orang yang dialami WNI di Kota Jeju, Korea yang direkrut dan dikirimkan oleh WNI. Meski, sudah patut diduga, terjadinya kasus ini melibatkan banyak oknum institusi publik sebagai ciri khas aktivitas mafia dalam human trafficking.
Atas dasar informasi itu, aparat keamanan baru mulai bekerja melakukan proses pemanggilan saksi dan melakukan interogasi kepada korban dan terdakwa. Sebagai gambaran dari proses rekruimennya menurut para korban, dirinya telah dijanjikan akan diberangkatkan ke Korea oleh tersangka untuk diperkerjakan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan gaji 80.000-100.000 Won per hari. Namun setibanya di Korea, para korban dipekerjakan di perkebunan (memanen sayuran lobak).
Rupanya para korban ditawari oleh salah seorang yang punya jabatan direktur dari salah satu kantor pengerah tenaga kerja yang sehari-hari bertindak sebagai kepala divisi Korea. Dengan modal pengetahuan dan relasi tentang tata cara bekerja ke Korea, lancarlah semua urusan meski sebenarnya orang ini belum mendapat job order dari negara tujuan.
Dengan sigap, dia melakukan proses rekrutmen terhadap Calon TKI dari berbagai wilayah NTB, Jabar, Jateng sampai sejumlah 15 orang. Apa yang terjadi kemudian? Meski para calon TKI sudah melunasi biaya keberangkatan, bahkan hampir secara umum dilakukan dengan cara mencicil dari total sejumlah 60 sampai dengan 110 juta, mereka tetap less job sesampai di tempat tujuan. Bahkan mereka harus hidup berpencar-pencar karena menghindari kejaran polisi setempat.
Saatnya Berbenah
Akhirnya, yang diperlukan saat ini bukan lagi berdebat siapa yang paling bertanggung jawab. Akan tetapi, secara simultan, mempercepat program kerja prioritas. Misalnya dalam konteks pencegahan, mau tidak mau PTSP harus jalan. Ego sektoral terutama institusi-institusi vertikal harus dihilangkan. Di sinilah kemudian dibutuhkan peran kementerian koordinator untuk mengoordinasikan. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di unit PTSP agar tidak ada kendala-kendala birokrasi. Terutama SDM yang masih belum siap bekerja dalam satu atap lantaran masih terkendala sektoral birokrasi.
Sehingga jika hasil survei tahun 2015 ditemukan masih belum bergabungnya 6 atau 7 sektor dalam satu unit layanan, hal ini kemudian bisa ditanggulangi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan asistensi pada pemerintah di tingkat Kecamatan dan desa untuk memastikan adanya kebijakan yang sama, terkait pengendalian terhadap menjamurnya lembaga-lembaga yang diberi kewenangan proses rekrutmen tenaga kerja. Langkah ini harus diambil agar kendali tetap di pemerintah sampai di tingkat bawah.
Jaringan pemerintah di tingkat paling bawah sampai dengan pemerintah provinsi harus difungsikan. Seperti gugus tugas TPPO. Aneka lembaga layanan yang selama ini telah bekerja keras mendukung lembaga-lembaga sektoral harus secara intensif dilibatkan, jangan justru ditinggal, karena sudah terbukti bahwa kerja pemberantasan TPPO tidaklah mudah. Maka proses pelibatan masyarakat sipil adalah bagian penting dari layanan public, termasuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan anti perdagangan orang di masyarakat dan lembaga pendidikan perlu dioptimalkan.
Dalam konteks penanganan korban, langkah konkret menuju pemulihan prima harus terus ditingkatkan. Meski saat ini telah ada lembaga-lembaga yang secara eksis dibentuk pemerintah, seperti P2TP2A, faktanya, mereka juga masih membutuhkan organ lain. Maka, lagi-lagi, tidak ada pilihan lain, sistem kerjanya perlu dilakukan perubahan agar sistem koordinasi dengan lembaga masyarakat yang juga melakukan fungsi kerja layanan bisa diintegrasikan. Sistem pemulihan yang tersedia harus dioptimalkan menuju pemulihan yang utuh, yaitu dengan mengaktifkan peran keluarga, masyarakat dan korban itu sendiri.
Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka memahami secara utuh bahaya human trafficking, serta bersedia membangun unit pengaduan di masyarakat. Dengan pemahaman yang bermuara pada kepedulian yang tinggi, siapapun bisa mencegah terjadinya human trafficking. Masyarakat harus diajak peduli dan bersedia melaporkan jika ditemukan ada indikasi upaya-upaya pemalsuan dan lainnya terkait persyaratan calon TKI.
Unit-unit pengaduan berbasis masyarakat ini, sejak semula aktif mengajak komunitasnya untuk “mengadu” jika ada masalah. Pemahaman bahwa mengadu bukan aib, tapi bagian dari kewajiban masyarakat harus digalakkan. Pola ketidakpedulian masyarakat juga harus berubah.
Tentu pengaduan-pengaduan ini harus direspons oleh pemerintah. Tetapi jika tidak direspon, maka masyarakat bisa menggunakan lembaga Ombudsman untuk mewakili kepentingannya. Pada saat yang sama, kementerian terkait dan lembaga legislatif secara strategis perlu melakukan upaya-upaya perbaikan di konteks kebijakan, antara lain dengan merevieu UU perlindungan pekerja di dalam negeri dan mengkritisi UU perlindungan buruh migran di luar negeri.[]
Anggota Ombudsman RI 2016-2021, sebelumnya sebagai Komisioner Komnas Perempuan 2007-2009 dan 2010-2014.
==========
Tulisan ini terbit di Koran Sindo pada Kamis, 9 Juni 2016