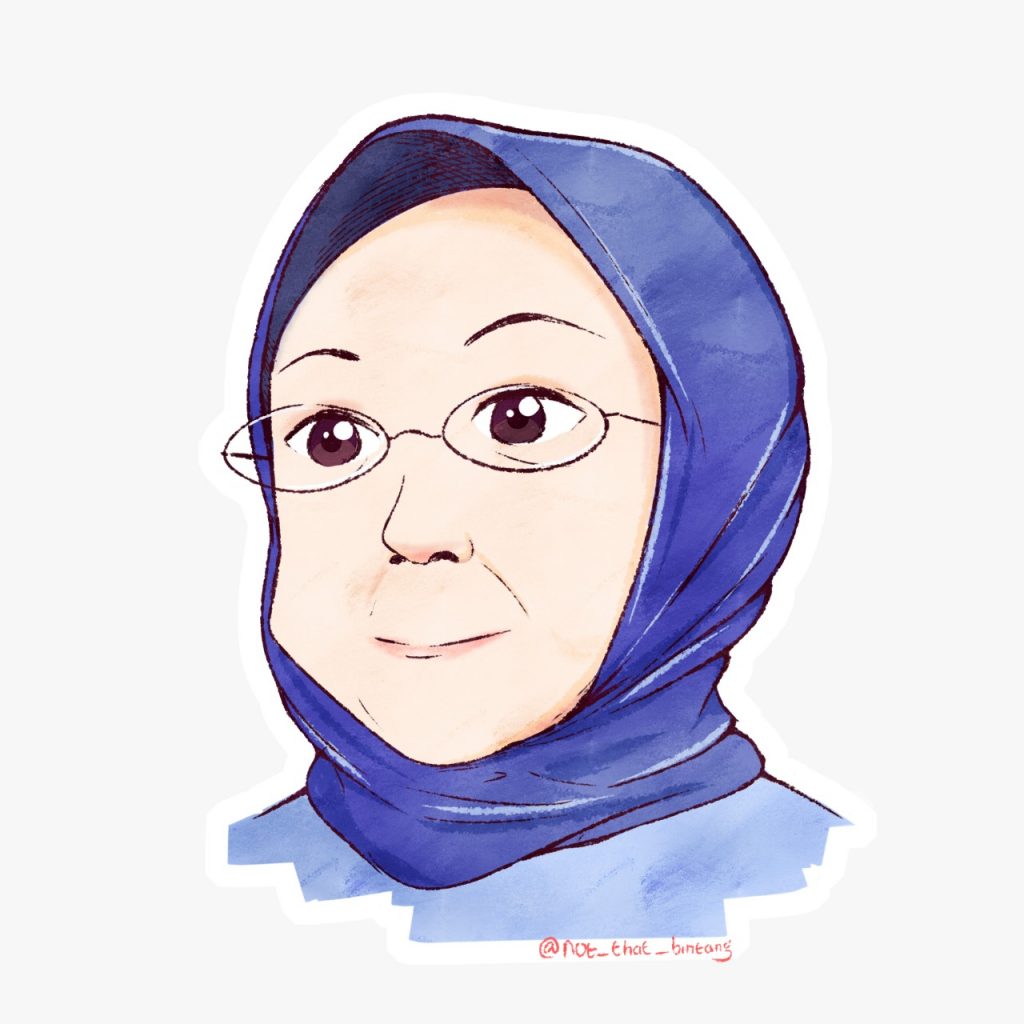Oleh: Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.
Maraknya kasus kekerasan seksual yang bertebaran di media, agaknya tidak cukup menghidupkan nurani para pemangku kebijakan untuk segera memberikan perlindungan hukum dan penjaminan terhadap korban kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tak kunjung disahkan. Sejatinya, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang mengalami penyiksaan. Lalu mengapa RUU TPKS masih berlarut-larut?
Terhitung 5 tahun lamanya RUU TPKS diperjuangkan oleh Komnas Perempuan dan sejumlah komunitas pegiat kesetaraan gender. Komnas Perempuan menyusun naskah akademiknya mulai tahun 2012-2015, kemudian diajukan tahun 2016 dengan judul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang kita kenal hari ini sebagai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Alih-alih mendapatkan perhatian, politikus senayan justru beranggapan bahwa rancangan undang-undang ini sulit dibahas dan cenderung mengada-ngada.
Sementara angka korban setiap tahunnya terus meningkat. Tercatat, Komnas Perempuan menerima sekitar 4.200 laporan kekerasan seksual tahun 2021, angka tersebut hampir dua kali lipat dari angka kasus tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Namun kita tahu bahwa angka tersebut sama halnya seperti gunung es, ada bagian yang terlihat di permukaan dan ada yang tak terlihat lebih banyak di dalamnya.. Kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit jumlahnya dari fakta realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya uluran tangan pemerintah kepada korban untuk berani menyuarakan serta meminta keadilan.
Diversifikasi Kebijakan Hukum Kekerasan Seksual
Sejumlah peraturan perundang-undangan memang telah mengatur persoalan kekerasan seksual, tetapi semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih harus dilengkapi hukum materil maupun formal (guna menutup celah kekosongan hukum), termasuk menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penanganan yang berpihak kepada korban.
KUHP, UU PKDRT, UU HAM, UU PTPPO, Konvensi Anti Penyiksaan, UU Perlindungan Anak, UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki ruang lingkup kekerasan seksual yang terbatas. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan paksa, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.
Diversifikasi aturan yang banyak ini menyebabkan multi tafsir sehingga tidak relevan dengan tujuan dibuatnya hukum. Tujuan dibuatnya hukum untuk memberi kepastian dan perlindungan. Jika celah ini masih ada, maka korban tidak akan mendapatkan kebermanfaatan hukum. Aturan-aturan yang diversifikasi dan multi tafsir tidak bisa menyelesaikan kekerasan seksual yang mereka hadapi.
Ketimpangan Relasi Kuasa
Kekerasan seksual adalah kasus yang pelik dan rumit, karena sampai sekarang orang lebih banyak menyalahkan korban. Yang perlu digaris bawahi bahwa RUU TPKS ini untuk masyarakat yang teraniaya, sekalipun diupayakan oleh komunitas yang lebih banyak diikuti oleh perempuan. Hal ini karena korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Kekerasan seksual terjadi akibat cara pandang penguasaan terhadap tubuh karena adanya kekuatan (power) dan daya paksa ingin diaplikasikan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Relasi demikian membuka peluang menguasai, objektifikasi, dan menundukkan salah satu pihak. Pelakunya bisa siapa saja dan bahkan orang terdekat sekalipun yang memiliki kuasa di atas korban. Namun bias budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kategori kelas nomor dua, menyebabkan perempuan menjadi kelompok paling rentan.
Pentingnya Persetujuan
Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam RUU TPKS selalu diidentikkan dengan makna melegalkan perzinahan. Persetujuan (consent) dalam hukum berhubungan dengan prinsip determinasi atau kehendak bebas (free will) yakni memberi pilihan kepada seseorang antara melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Jika seseorang melakukan kejahatan maka akan terdapat konsekuensi, baik hukum maupun kaidah-kaidah sosial lain. Jika frasa ini ingin dikaitkan dengan sexual consent, maka consent tersebut dilihat dari perspektif korban dengan kehendak bebasnya seperti tidak adanya tekanan, kedudukan yang tidak seimbang, dan batasan-batasan lainnya. Berdasarkan prinsip kehendak bebas, apabila korban kehilangan batasan-batasannya (tidak memiliki consent) maka pelaku disamakan dengan melakukan kejahatan.
Catatan penting untuk menentukan consent atau tidaknya didasarkan pada teori fektimologi, yakni harus ada yang disampaikan, dirasakan, direfleksikan oleh korban atas apa yang ia alami. Dalam tindak pidana harus ada seseorang yang dinyatakan sebagai korban yang sifatnya individual, bukan kelompok. Sekalipun kehendak bebas itu diberikan bukan berarti seseorang bisa melakukan segalanya. Frasa yang sama namun dalam istilah berbeda, sebelumnya juga terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yakni “ketidaksepahaman”.
Pendidikan Kritis
Selama ini korban sendirian ketika menghadapi kasus kekerasan seksual, bahkan kadang-kadang tidak hanya masyarakat, keluarga saja pun tidak memberi dukungan. Seyogyanya, ekologi sistem yang memberi dukungan sangat penting dalam regulasi. Kita tidak boleh membiarkan korban dalam ketidaktahuannya, karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Ketika semua korban diam dan tidak diproses hukum, pelaku akan merasa bahwa yang ia lakukan benar dan bukan kejahatan. Untuk memberi dukungan agar korban berani melaporkan dan mengakomodasi kebutuhannya, dibutuhkan suatu sistem yang menjamin korban.
Menciptakan suatu sistem serta ekologi tersebut membutuhkan daya kritis. Pendidikan kritis tidak datang begitu saja, terutama tentang pola-pola kekuasaan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Relasi ketimpangan kekuasaan ini bukan hanya ada di masyarakat, tapi juga ada dalam teks-teks agama yang ditafsirkan sembarangan. Tafsir terhadap teks keagamaan tersebut membutuhkan nalar kritis tentang hakikat kemanusiaan, hakikat keadilan bagi manusia, dan di mana kita harus meletakkan perempuan sebagai manusia. RUU TPKS bukan sekedar berbicara aturan, melainkan nilai keilahian dan kemanusiaan. Hal ini adalah wujud komitmen Indonesia baik secara nasional maupun global untuk menjadi negara bebas kekerasan.
Pelayanan Satu Atap
Jika mau memahami bahwa fakta kekerasan seksual itu terjadi dan nyata serta merupakan kebutuhan, rasanya tidak ada alasan untuk melakukan penolakan. Pengalaman perempuan perlu didengarkan sebagai kelompok mayoritas yang mengalami kasus kekerasan seksual. Bagi siapapun yang siap melapor, harus mendapat keamanan dan perlindungan hukum. Perlindungan dalam hal ini adalah sistem pelayanan satu atap. Di mana korban mendapatkan pelayanan secara komprehensif, mulai dari proses melaporkan, berhadapan dengan hukum hingga pemulihan korban. Banyaknya kasus kekerasan, adanya celah dalam aturan hukum kekerasan seksual sebelumnya, ketimpangan relasi kuasa, dan hilangnya nalar kritis dalam memandang kasus kekerasan telah mengantarkan Indonesia pada gerbong darurat. Bukan hanya aturan-aturan yang penting diperjuangkan tetapi bagaimana menjalankan aturan ini menggunakan perspektif korban kekerasan seksual.
Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk membangun semangat yang sama dengan masyarakat sipil karena undang-undang ini dibangun dengan tangis dan jerit keluarga korban serta masyarakat yang sangat membutuhkan perlindungan dari sisi hukum.
Pandangan tentang pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi melalui laman Youtube Sekretariat Presiden tertanggal 4 Januari 2020, bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama, utamanya kekerasan seksual pada perempuan. Presiden juga memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU TPKS sebagai upaya percepatan. Serta meminta gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI, sehingga proses pembahasan nantinya bisa masuk pada pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian dan menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
Langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS oleh Presiden, saya kira harus disambut baik oleh DPR dengan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022, termasuk mengikutsertakan partai-partai yang masih “galau” atau yang masih bersikap “abu-abu” untuk duduk bersama. Ke depan, saya harap pemerintah juga harus terbuka dan partisipatif dalam rangka pembahasan lebih lanjut, sehingga bisa menghimpun apabila ada muatan-muatan yang saaat ini belum terakomodasi. Jika draf yang diberikan oleh DPR RI nantinya belum cukup, maka pemerintah harus mengambil inisiatif untuk melengkapinya. Mari bergandengan tangan, sahkan RUU TPKS! []
Direktur Perkumpulan JalaStoria Indonesia