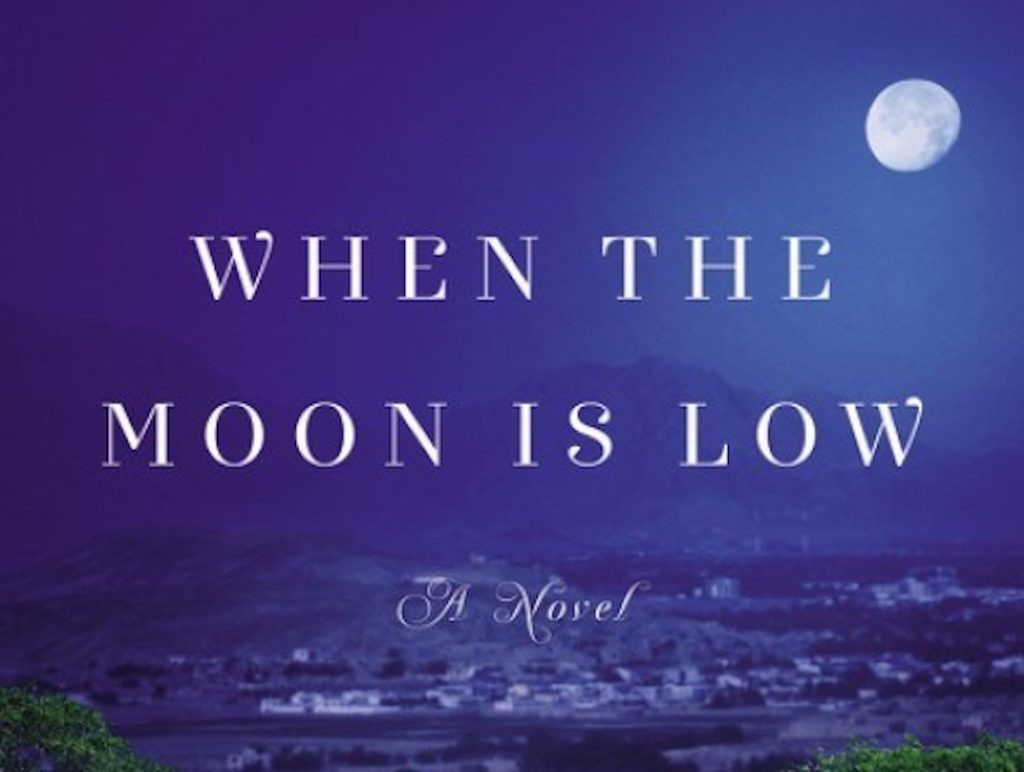Perjuangan perempuan tidak harus selalu direpresentasikan kehadirannya di pos terdepan: membawa spanduk atau berbicara di depan forum publik, meskipun yang sedemikian itu banyak dijumpai.
Sebab, sejatinya, perjuangan perempuan, sudah dimulai sejak ia membuka mata dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Fereiba salah satunya.
Perjuangannya sudah dimulai sejak tali pusarnya terlepas dari rahim sang ibu. Hingga seiring waktu berjalan, Fereiba mulai menyadari betapa kekuatan diri tumbuh justru saat krisis mendera.
Nadia Hashimi, dalam novelnya: When the Moon Is Low, menggambarkan perjuangan Fereiba itu, seorang ibu yang harus meninggalkan Afganistan setelah suaminya dibunuh oleh Taliban.
Perjalanan mencari suakanya tidak hanya menampilkan gambaran mengenai hidup perempuan tanpa suami, marjinal (dalam budaya patriarki Taliban), dan menderita.
Tetapi juga menggambarkan perjalanan penuh bahaya ke Eropa dengan tiga anak yang salah satunya mesti terpisah dan menjalani hidup seorang diri mencari keluarganya.
—–
Sejak kecil Fereiba disibukkan dengan urusan pengasuhan adik-adik tirinya dan juga pekerjaan rumah tangga.
KokoGul, ibu tiri Fereiba, bahkan memblokade akses pendidikan untuknya dan berkeras bahwa ketenteraman dan kepuasan dapat dicapai Fereiba hanya dengan berkutat di dalam rumah.
Berapa banyak kebiasaan berpikir model itu yang kemudian merenggut kesempatan perempuan muda untuk bersekolah? Banyak! dan Fereiba memutus rantai kebiasaan itu.
Kenyataan bahwa adik-adiknya bersekolah sementara ia tidak, sama sekali tidak mengecilkan hatinya.
Setelah terlambat enam tahun, Fereiba berkesempatan mengenyam pendidikan formal meski dalam benaknya ia berpikir: “I could have been their caretaker. Here, I was their peer.”
Petualangan mencari suaka Fereiba dan ketiga anaknya di tengah adangan Taliban, yang disebutnya sebagai the turbaned tyrants, sungguh menampilkan kekuatan perempuan dan anak-anak yang luar biasa di tengah krisis yang menerpa.
Jika Mohsin Hamid dalam Exit West menawarkan alternatif pencarian suaka melalui pintu-pintu ajaib.
Hashimi mengambil jalan lebih nyata: betapa nyawa adalah harga yang murah dalam pelarian para pengungsi yang harus menyelamatkan diri dari konflik dan perang di negaranya melalui perjalanan yang amat berbahaya.
Jika laporan surat kabar memuat berita mengenai pengungsi, maka dari When the Moon Is Low-lah rincian mengenai pengalaman pribadi seorang Fereiba dan anaknya, Saleem, dapat memberi gambaran utuh mengenai betapa nyatanya penderitaan para eksodus.
—–
Sebetulnya, sudut pandang antara Fereiba dan anaknya, Saleem, memberi perspektif yang berbeda antara isi pikiran ibu dan anaknya.
Seorang ibu yang harus dihadapkan pada dilema meneruskan perjalanan ke Italia tanpa anak sulungnya ibarat buah simalakama.
Keterkejutan juga bukan tak dihadapi Saleem, yang perjalanannya menjadi dua kali lebih brutal tanpa ibu dan dokumen palsunya.
Ia harus berjuang menyeberangi separuh benua Eropa tanpa dokumen apa pun dan berkejaran dengan aparat.
Sebab bagi Saleem, kembali ke Afganistan bukanlah ide bagus malah lebih mirip mimpi buruk.
Jika Exit West menawarkan dunia baru yang memungkinkan pengungsi dan penduduk setempat berdampingan.
When the Moon Is Low menghamparkan kenyataan betapa untuk sampai dengan selamat mengarungi samudera menumpang truk atau kapal karet ke daratan berikutnya saja sudah menjadi karunia yang mendekati keajaiban.
Untuk jadi perempuan, apalagi menjadi seorang ibu di rezim Taliban, melakukan eksodus merupakan keputusan yang lebih masuk akal.
Jika usaha mencari suaka merupakan usaha yang setengah tak manusiawi, maka menjadi perempuan pencari suaka membutuhkan kekuatan fisik dan psikis yang lebih besar.
Terlebih bila perjalanan itu dilakukan sembari menyambung nyawa bayi yang tengah menyusu, anak-anak yang mesti bertahan di tengah perjalanan yang sulit, dan diri sendiri, yang harus menjadi benteng perlindungan bagi anak-anaknya.
My worst fear is the same as my biggest hope—separation from my children… I pray at some checkpoints that my children be granted asylum even if I am sent back. At other checkpoints, I pray we are sent back together. Cornered mother pray for strange things (Hal. 38)
Petikan ini boleh jadi memunculkan pertanyaan: Bagaimana mungkin dunia abai pada penderitaan dan krisis kemanusiaan tak berkesudahan?
Bagaimana bila itu terjadi pada kita?
Sudah berapa banyak pengungsi yang mesti tetap berjalan meski terpisah dengan anak-anaknya dan tak menghukum diri karenanya?
—–
Nurhadianty Rahayu
Perempuan, ibu, pengajar, penerjemah lepas, dan budak kapitalis biasa yang tak istimewa